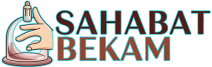Cerebral Palsy (CP) merupakan sekumpulan gangguan saraf yang tidak progresif dan memengaruhi gerak tubuh, koordinasi, serta postur. Kata “cerebral” merujuk pada otak, sementara “palsy” mengacu pada kelemahan otot atau kesulitan dalam mengendalikan otot. CP terjadi akibat kerusakan otak atau perkembangan otak yang tidak normal, yang berlangsung sebelum, saat, atau sesaat setelah kelahiran, ketika otak masih dalam masa pertumbuhan.
CP merupakan kondisi yang berasal dari gangguan pada otak dan mempengaruhi sistem saraf, terutama bagian yang mengatur gerakan tubuh. Anak-anak dengan CP mengalami kesulitan dalam melakukan aktivitas motorik sadar, seperti mengambil sesuatu, berjalan, atau berbicara. Gerakan mereka bisa terasa kaku, tidak terkendali, atau terlalu lemah.
Jenis-jenis CP berdasarkan gangguan pergerakan utama terdiri atas:
Secara global, diperkirakan sekitar 1 sampai 4 kasus dari setiap seribu kelahiran hidup terjadi pada bayi yang mengalami CP. Beberapa sumber menyatakan bahwa sekitar 18 juta orang di seluruh dunia hidup dengan kondisi ini di semua kelompok usia. Terdapat perbedaan yang cukup besar dalam tingkat prevalensi CP antara negara dengan pendapatan tinggi (High-Income Countries – HICs) dan negara dengan pendapatan rendah serta menengah (Low- and Middle-Income Countries – LMICs).
Di negara-negara berpenghasilan tinggi (HICs), angka kejadian CP umumnya lebih rendah, yaitu sekitar 1,5 hingga 2,5 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Hal ini disebabkan oleh kemajuan dalam pelayanan kesehatan prenatal, persalinan, dan neonatal (seperti peningkatan kualitas perawatan intensif untuk bayi prematur dan dengan berat lahir rendah), yang membantu mengurangi faktor risiko penyebab CP. Beberapa studi melaporkan adanya penurunan angka prevalensi CP di HICs dalam beberapa dekade terakhir.
Di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah (LMICs), prevalensi cerebral palsy (CP) dilaporkan lebih tinggi, bahkan dapat mencapai 3,4 hingga 5,6 kasus per 1.000 kelahiran hidup. Beberapa faktor yang berkontribusi pada tingginya angka prevalensi tersebut di antaranya adalah akses yang terbatas terhadap pelayanan kesehatan prenatal dan persalinan bermutu, kurangnya fasilitas perawatan neonatal yang memadai, gizi ibu yang tidak memadai, tingkat infeksi yang lebih tinggi, serta risiko trauma saat proses kelahiran.
Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia pada tahun 2018, tingkat kejadian cerebral palsy (CP) di Indonesia mencapai 0,09% dari total anak berusia 24 hingga 59 bulan. Dengan kata lain, dari setiap seribu anak dalam kelompok usia 2 hingga 5 tahun, terdapat sekitar 0,9 anak—yang dapat dibulatkan menjadi 1 anak—yang terdiagnosis mengalami CP. Angka tersebut setara dengan 9 kasus untuk setiap 1.000 kelahiran. Jika dibandingkan dengan negara-negara maju, prevalensi CP di Indonesia tergolong lebih tinggi.
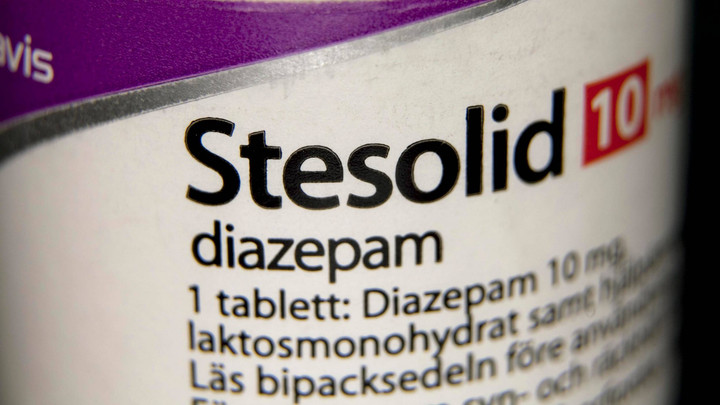
Anak yang mengalami Cerebral Palsy (CP) memerlukan layanan kesehatan yang menyeluruh dan berkelanjutan seumur hidup mereka. Sayangnya, banyak keluarga yang menghadapi tantangan berat akibat beban finansial dan ekonomi yang tinggi, sehingga perjalanan mereka seringkali seperti “jalan berliku”. Hambatan-hambatan ini menjadi penghalang utama bagi anak-anak dengan CP untuk mendapatkan perawatan yang diperlukan guna mencapai potensi penuh mereka. Perawatan bagi anak dengan CP tidak hanya berkutat pada pemberian obat, tetapi juga mencakup berbagai intervensi medis dan rehabilitasi yang kompleks, terus-menerus, serta biayanya cukup mahal.
Di Indonesia, BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan nasional yang memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Meski demikian, terdapat keterbatasan pada cakupan untuk terapi rehabilitasi. Sebagai contoh, jumlah sesi terapi bisa dibatasi per minggu atau per bulan, sementara anak dengan kondisi cerebral palsy (CP) biasanya membutuhkan frekuensi terapi yang lebih sering. Tidak semua jenis atau merek alat bantu serta peralatan adaptif sepenuhnya dijamin oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Terdapat batasan harga maupun jenis alat yang dapat diajukan klaimnya, sehingga keluarga harus menanggung biaya tambahan. Selain itu, beberapa obat khusus yang harganya mahal atau belum termasuk dalam daftar obat standar juga tidak sepenuhnya ditanggung oleh program tersebut.
Selain kendala biaya, keterbatasan akses secara geografis serta kondisi infrastruktur yang kurang memadai juga menjadi tantangan penting lainnya bagi keluarga anak penderita CP dalam memperoleh layanan kesehatan yang diperlukan. Wilayah tempat tinggal dan mutu infrastruktur di sekitarnya menentukan seberapa gampang atau sulitnya mereka menjangkau fasilitas perawatan yang dibutuhkan.
Indonesia, sebagai sebuah negara kepulauan yang besar, menghadapi kesenjangan signifikan dalam akses layanan kesehatan antara wilayah perkotaan dan daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Perawatan untuk cerebral palsy (CP) memerlukan fasilitas khusus seperti klinik fisioterapi, terapi okupasi, dan terapi wicara yang dilengkapi dengan peralatan yang memadai serta didukung oleh tenaga ahli yang berpengalaman dan terlatih.
Di wilayah perkotaan, fasilitas ini umumnya tersedia, namun sulit ditemukan atau bahkan tidak tersedia sama sekali di daerah-daerah terpencil. Karena keterbatasan tersebut, anak-anak di wilayah itu sering kali tidak memperoleh intervensi awal dan berkelanjutan yang sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan mereka.
Selain kendala finansial dan geografis, minimnya tenaga medis serta spesialis yang ahli menjadi salah satu tantangan utama dalam memastikan akses pelayanan kesehatan bagi anak dengan cerebral palsy (CP). Kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia di sektor kesehatan sangat berpengaruh terhadap apakah anak-anak tersebut dapat memperoleh perawatan yang tepat dan menyeluruh. Penanganan anak dengan CP memerlukan tim medis multidisiplin yang terdiri dari berbagai bidang keahlian. Sayangnya, jumlah tenaga profesional yang memiliki pengalaman di bidang ini masih sangat terbatas, terutama di luar pusat-pusat perkotaan besar.
Stigma dan diskriminasi kerap menjadi penghalang yang lebih menyakitkan serta merugikan dibandingkan hambatan fisik atau masalah finansial. Bagi anak yang memiliki cerebral palsy (CP) beserta keluarganya, adanya stigma tersebut bisa menghambat akses mereka terhadap layanan kesehatan yang sejatinya merupakan hak mereka.
Stigma serta diskriminasi tidak muncul tanpa sebab; umumnya berasal dari minimnya pemahaman dan kesadaran masyarakat, termasuk juga di kalangan tenaga kesehatan, mengenai kondisi cerebral palsy (CP). Banyak orang masih memiliki anggapan yang salah tentang CP.
Sebagian orang mengaitkan CP dengan keterbelakangan mental, meski sebenarnya banyak anak yang memiliki CP mempunyai tingkat kecerdasan yang normal. Kesalahan anggapan ini menciptakan suasana yang tidak kondusif dan sering kali menyebabkan anak-anak tersebut diasingkan. Masyarakat luas umumnya belum memahami bahwa CP merupakan gangguan neurologis non-progresif akibat kerusakan otak yang terjadi sejak dini, bukan penyakit infeksi atau menular.
Orang tua anak yang mengalami CP (Cerebral Palsy) kerap menghadapi stigma sosial, di mana mereka dituding atau dikaitkan dengan kondisi yang dialami anaknya. Situasi ini memperberat beban psikologis yang sudah mereka rasakan sebagai orang tua dari anak dengan CP. Untuk menghilangkan stigma tersebut, penting dilakukan kampanye edukasi publik serta pelatihan berkelanjutan bagi tenaga medis.

Di Indonesia, hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan, termasuk bagi anak-anak yang mengalami cerebral palsy (CP), dilindungi oleh berbagai ketentuan perundang-undangan. Kerangka hukum nasional ini menjadi dasar dalam upaya perlindungan serta pemenuhan hak-hak mereka. Landasan utama perlindungan hak atas kesehatan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 dengan jelas menyatakan bahwa,
Setiap individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang sejahtera secara fisik dan mental, memiliki tempat tinggal, mendapatkan lingkungan hidup yang sehat serta layak, dan berhak atas pelayanan kesehatan.
Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang, tanpa memandang kondisi fisiknya, berhak secara dasar atas pelayanan kesehatan. Negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menyediakan serta menjamin akses terhadap layanan kesehatan yang memadai bagi seluruh warganya, termasuk anak-anak yang memerlukan perawatan khusus, seperti mereka yang hidup dengan CP.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 mengenai Penyandang Disabilitas merupakan langkah penting dalam upaya melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Indonesia. Dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a disebutkan bahwa, “Setiap Penyandang Disabilitas memiliki hak: a. hidup; b. bebas dari perlakuan diskriminatif; …”
Anak yang memiliki CP merupakan penyandang disabilitas. Pasal ini menegaskan hak mereka untuk menjalani kehidupan yang layak dan, yang lebih penting, bebas dari segala bentuk diskriminasi di semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal mengakses layanan kesehatan. Hal ini menjadi dasar hukum untuk menuntut perlakuan yang setara dan adil di sarana pelayanan kesehatan.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan memperkuat tanggung jawab pemerintah dan pihak terkait dalam menyediakan layanan kesehatan yang merata, membangun sistem kesehatan yang mampu beradaptasi, serta memperkuat pelayanan kesehatan primer. Dengan penekanan pada pelayanan kesehatan dasar, diharapkan dapat meningkatkan deteksi dini dan penanganan awal kasus CP di tingkat masyarakat.
Meningkatkan akses layanan kesehatan untuk anak dengan cerebral palsy (CP) merupakan upaya yang melibatkan berbagai aspek dan memerlukan komitmen kuat dari semua pihak terkait. Pemerintah harus menyediakan anggaran kesehatan yang cukup serta khusus untuk pelayanan anak berkebutuhan khusus, termasuk mereka dengan CP, sekaligus mendorong pengembangan skema asuransi kesehatan swasta atau subsidi silang yang bisa menanggung biaya layanan yang belum sepenuhnya dicakup oleh Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Selain itu, pemerintah juga perlu mendukung pembentukan serta penguatan tim medis multidisiplin di setiap rumah sakit dan pusat rehabilitasi yang menangani kasus CP. Tim tersebut wajib bekerja sama secara intensif dalam menyusun serta mengevaluasi program perawatan yang diberikan.
Pemerintah harus secara aktif membangun atau meningkatkan pusat-pusat rehabilitasi di setiap provinsi, bahkan hingga tingkat kabupaten atau kota. Pusat rehabilitasi tersebut perlu menyediakan layanan yang terpadu—seperti fisioterapi, terapi okupasi, terapi wicara, layanan gizi, dan psikologi—dengan perlengkapan yang mencukupi. Seluruh fasilitas kesehatan, dari Puskesmas sampai rumah sakit rujukan, perlu didesain atau direnovasi agar dapat diakses dengan mudah oleh penyandang disabilitas.
Di wilayah terpencil, dapat diadakan program layanan kesehatan keliling yang secara rutin mengirimkan tim medis dan terapis. Selain itu, tele-rehabilitasi (terapi jarak jauh melalui panggilan video) bisa menjadi solusi inovatif untuk konsultasi dan pemantauan, sehingga mengurangi kebutuhan akan perjalanan fisik.
Mengubah persepsi masyarakat merupakan langkah penting untuk membangun lingkungan yang inklusif bagi anak dengan CP. Upaya ini bisa dilakukan dengan melibatkan pihak sekolah, Puskesmas, dan tokoh-tokoh masyarakat dalam menyampaikan informasi yang benar mengenai CP. Kerja sama ini berpotensi mendukung terciptanya program inklusi di lingkungan pendidikan maupun sekitar tempat tinggal.