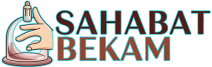Dalam beberapa tahun terakhir, keberlanjutan telah muncul sebagai fokus kritis bagi bisnis di seluruh dunia. Meskipun keberlanjutan lingkungan dan ekonomi sering mendominasi pembahasan, konsep tersebut adalah
Manajemen Sumber Daya Manusia Berkelanjutan (SDM Berkelanjutan)
sedang mendapatkan momentum sebagai komponen penting dalam kesuksesan organisasi jangka panjang.
SDM yang berkelanjutan mengintegrasikan aspek sosial, lingkungan, dan ekonomi ke dalam praktik SDM untuk memastikan kesejahteraan karyawan, ketahanan organisasi, dan dampak terhadap masyarakat.
Artikel ini membahas prinsip, manfaat, tantangan, dan tren masa depan dari Human Resource yang Berkelanjutan (Sustainable HR), yang didukung oleh penelitian akademis dan wawasan industri.
Memahami SDM yang Berkelanjutan
HR berkelanjutan mengacu pada penyesuaian strategis praktik SDM dengan tujuan keberlanjutan, memastikan bahwa pengelolaan tenaga kerja memberikan kontribusi positif bagi karyawan, perusahaan, dan masyarakat secara luas.
Berbeda dengan HR tradisional yang terutama berfokus pada efisiensi dan produktivitas, Sustainable HR menekankan penciptaan nilai jangka panjang, praktik ketenagakerjaan yang etis, serta pengembangan karyawan.
Menurut Ehnert (2009), Sustainable HR adalah “pola kebijakan dan praktik SDM formal maupun informal yang bertujuan untuk memungkinkan pencapaian tujuan organisasi sekaligus mempertahankan basis SDM dalam jangka waktu yang lama serta mengendalikan dampak samping negatif.”
Evolusi Manajemen Sumber Daya Manusia Berkelanjutan (Sustainable HR) sangat terkait dengan gerakan ekonomi, sosial, dan lingkungan yang lebih luas.
Seiring berjalannya waktu, perubahan dalam hak pekerja, etika dan tata kelola perusahaan, serta kepedulian terhadap keberlanjutan global telah membentuk cara organisasi mengelola tenaga kerja saat ini. Memahami kisah-kisah utama di balik Sumber Daya Manusia yang Berkelanjutan memberikan wawasan mengapa hal tersebut menjadi fondasi strategi bisnis modern.
Akar Sustainable HR dapat ditelusuri kembali ke revolusi industri, sebuah periode yang ditandai oleh industrialisasi pesat dan kondisi kerja yang keras. Para pekerja pabrik, termasuk wanita dan anak-anak, harus bertahan dengan jam kerja yang terlalu panjang, lingkungan yang tidak aman, serta upah yang minimal. Eksploitasi tenaga kerja menyebabkan pemberontakan buruh awal dan terbentuknya serikat pekerja, yang memperjuangkan upah yang adil, jam kerja yang masuk akal, serta tempat kerja yang lebih aman.
Salah satu tonggak sejarah yang paling menonjol adalah dibentuknya Undang-Undang Standar Tenaga Kerja yang Adil (Fair Labor Standards Act) tahun 1938 di Amerika Serikat, yang memperkenalkan minggu kerja 40 jam dan undang-undang upah minimum.
Reformasi tenaga kerja awal ini meletakkan dasar bagi prinsip-prinsip utama Sustainable HR, kompensasi yang adil, hak-hak karyawan, dan keselamatan tempat kerja yang kemudian berkembang di masa mendatang. Pertumbuhan ekonomi pasca Perang Dunia II membawa gelombang baru dalam pola pikir korporat.
Perusahaan-perusahaan mulai menyadari bahwa tanggung jawab mereka tidak hanya terbatas pada mencari keuntungan, tetapi juga mencakup dampak terhadap masyarakat. Konsep Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) kemudian muncul, menekankan praktik bisnis yang etis, filantropi, dan keterlibatan dengan masyarakat.
Salah satu momen paling berpengaruh dalam sejarah CSR adalah terbitnya esai Milton Friedman pada tahun 1970, di mana ia berpendapat bahwa tanggung jawab tunggal perusahaan adalah meningkatkan keuntungan para pemegang saham. Hal ini memicu debat sengit, yang kemudian melahirkan gerakan-gerakan kontra yang mengadvokasi teori pemangku kepentingan (stakeholder theory), gagasan bahwa perusahaan harus melayani karyawan, pelanggan, dan masyarakat secara umum, bukan hanya investor. Perubahan ideologis ini mempengaruhi praktik-praktik SDM, mendorong organisasi untuk mempertimbangkan kesejahteraan karyawan sebagai bagian dari kesuksesan jangka panjang mereka.
Kelahiran Green HR dan Kesadaran Lingkungan
Gerakan lingkungan hidup pada tahun 1960-an dan 1970-an membawa konsep keberlanjutan ke dalam agenda perusahaan. Pada tahun 1990-an, bisnis mulai mengintegrasikan kebijakan lingkungan ke dalam strategi SDM, yang kemudian melahirkan
SDM Hijau
.
Momen pentingnya adalah Laporan Brundtland dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (1987), yang mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai “memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.” Laporan ini mempengaruhi perusahaan-perusahaan untuk mengadopsi praktik-praktik sumber daya manusia yang ramah lingkungan, seperti mengurangi limbah kertas, mendorong kerja jarak jauh, serta menerapkan tempat kerja yang hemat energi.
Abad ke-20 akhir dan abad ke-21 awal menyaksikan munculnya ekonomi digital yang mengubah struktur kerja dan harapan karyawan. Ledakan perusahaan internet (dot-com) memperkenalkan budaya kerja fleksibel, tetapi juga menyebabkan burnout dan ketidakpastian pekerjaan. Kasus-kasus terkenal ketidakpuasan karyawan, seperti kontroversi tenaga kerja Foxconn (2010-an), mengungkapkan sisi gelap dari tuntutan produktivitas yang tidak terkendali. Sebagai respons, perusahaan-perusahaan seperti Google dan Salesforce mempelopori inisiatif kesejahteraan tempat kerja, menawarkan dukungan kesehatan mental, jadwal fleksibel, dan budaya inklusif. Pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) atas burnout di tempat kerja (2019) sebagai fenomena yang berkaitan dengan pekerjaan semakin memperkuat perlunya praktik SDM berkelanjutan yang mengutamakan kesehatan karyawan dalam jangka panjang daripada keuntungan jangka pendek.
Pandemi (2020-2022) menjadi momen penentu bagi SDM Berkelanjutan. Organisasi di seluruh dunia menghadapi tantangan yang belum pernah terjadi sebelumnya, transisi kerja jarak jauh, krisis kesehatan mental karyawan, dan ketidakstabilan ekonomi. Perusahaan yang sebelumnya telah berinvestasi dalam SDM Berkelanjutan, seperti Unilever, mampu beradaptasi lebih lancar dengan memprioritaskan keselamatan dan fleksibilitas karyawan. Covid-19 dan dampaknya menyoroti konsekuensi dari budaya kerja yang tidak berkelanjutan, dengan jutaan orang meninggalkan pekerjaan akibat kelelahan dan kurangnya keseimbangan hidup. Eksodus besar-besaran ini memaksa perusahaan untuk memikirkan ulang strategi retensi, sehingga memberikan penekanan yang lebih kuat pada prinsip-prinsip SDM Berkelanjutan seperti keamanan psikologis, pengembangan karier, dan kesetaraan upah.
Saat ini, Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkelanjutan berkembang sejalan dengan kerangka Kerangka Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) yang membuat perusahaan bertanggung jawab atas praktik ketenagakerjaan yang etis. Selain itu, kecerdasan buatan (AI) digunakan untuk meningkatkan pengalaman karyawan melalui analitik prediktif untuk retensi dan pembelajaran personal. Kisah SDM Berkelanjutan masih terus ditulis, dibentuk oleh perdebatan yang terus berlangsung mengenai hak pekerja lepas (gig worker), dampak otomatisasi terhadap pekerjaan, serta transisi angkatan kerja terkait iklim. Saat perusahaan menjalani tantangan-tantangan ini, pelajaran dari sejarah mengingatkan kita bahwa SDM Berkelanjutan bukan hanya sekadar tren, tetapi sebuah kebutuhan untuk membangun organisasi yang tangguh, etis, dan siap menghadapi masa depan.
Angkatan kerja yang berkelanjutan mengutamakan kesehatan karyawan, kesejahteraan mental, dan keseimbangan kehidupan kerja. Perusahaan yang berinvestasi pada program kesehatan, pengaturan kerja fleksibel, serta inisiatif manajemen stres mengalami tingkat keterlibatan dan retensi yang lebih tinggi (Gubler dkk., 2018). SDM berkelanjutan mendorong keragaman, kesetaraan, dan inklusi (DEI) dalam rekrutmen dan manajemen bakat. Organisasi yang menerapkan praktik perekrutan adil dan menghilangkan bias akan mendapat manfaat dari angkatan kerja yang lebih inovatif dan terlibat. Berinvestasi pada pertumbuhan karyawan memastikan kemampuan adaptasi organisasi dalam jangka panjang. SDM berkelanjutan mendorong pembelajaran sepanjang hayat melalui program peningkatan keterampilan, pelatihan ulang, dan pengembangan kepemimpinan. Menurut Forum Ekonomi Dunia (2023), perusahaan yang mengutamakan pembelajaran berkelanjutan lebih siap dalam menghadapi gangguan teknologi. Inisiatif SDM ramah lingkungan seperti kebijakan kerja jarak jauh, proses perekrutan tanpa kertas, dan praktik kantor berkelanjutan dapat mengurangi jejak karbon organisasi. SDM berkelanjutan juga mendukung upah yang adil, stabilitas pekerjaan, serta standar ketenagakerjaan yang etis.
Organisasi yang dikenal karena praktik SDM yang etis menarik bakat terbaik. Studi oleh LinkedIn (2022) menemukan bahwa 75% pencari kerja mempertimbangkan komitmen keberlanjutan sebuah perusahaan sebelum melamar. Karyawan yang merasa dihargai dan didukung lebih mungkin untuk bertahan di organisasi. Gallup (2021) melaporkan bahwa perusahaan dengan tingkat keterlibatan karyawan tinggi mengalami peningkatan laba sebesar 21%. SDM berkelanjutan mendorong adaptabilitas, membantu bisnis bertahan dari gangguan ekonomi dan sosial. Pandemi COVID-19 menyoroti pentingnya strategi ketahanan tenaga kerja, dengan perusahaan yang memprioritaskan kesejahteraan karyawan pulih lebih cepat (Deloitte, 2021).
Dengan meningkatnya undang-undang ketenagakerjaan dan regulasi ESG, Sumber Daya Manusia (SDM) Berkelanjutan memastikan kepatuhan sekaligus meminimalkan risiko hukum. Namun, SDM Berkelanjutan membutuhkan biaya tinggi, memerlukan investasi finansial besar di awal untuk mendapatkan keuntungan jangka panjang. Investasi dalam kesejahteraan karyawan dan inisiatif ramah lingkungan dengan biaya awal yang signifikan dapat membuat beberapa organisasi ragu, meskipun keuntungan jangka panjang sering kali melampaui pengeluaran awal. Beralih dari model SDM yang berorientasi laba menjadi berfokus pada keberlanjutan membutuhkan komitmen kepemimpinan dan transformasi budaya. Menghitung ROI dari inisiatif SDM Berkelanjutan bisa menjadi tantangan, karena manfaat seperti kepuasan karyawan bersifat tidak nyata (intangible).
Seiring dengan perkembangan bisnis, Sustainable HR terus berkembang lebih dalam dan mengintegrasikan AI serta Data-Driven HR. Analitik prediktif membantu menyesuaikan program kesejahteraan karyawan dan mengurangi pergantian tenaga kerja. Sustainable HR dapat memenuhi kebutuhan pekerja lepas dan kontrak. Pasca-pandemi, dukungan terhadap kesehatan mental seharusnya menjadi bagian standar layanan HR, dan karyawan yang berpindah antar peran akan membutuhkan pelatihan berkelanjutan untuk pengembangan keterampilan baru.
HR berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi perusahaan yang bertujuan mencapai kesuksesan jangka panjang. Dengan memprioritaskan kesejahteraan karyawan, praktik etis, dan tanggung jawab lingkungan, organisasi dapat membangun tenaga kerja yang tangguh dan siap menghadapi masa depan. Seperti yang disarankan oleh penelitian Kramar (2014), HR berkelanjutan merupakan jembatan antara kesuksesan korporat dan kemajuan sosial. Perusahaan yang menganut pendekatan ini tidak hanya akan berkembang secara ekonomi tetapi juga berkontribusi terhadap dunia yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan menerapkan HR berkelanjutan, bisnis dapat memastikan bahwa mereka tidak hanya menguntungkan tetapi juga bermakna, menciptakan tenaga kerja yang berkembang saat ini dan berkelanjutan di masa depan demi keuntungan bersama pemegang saham dan masyarakat.
Bacaan Lebih Lanjut:
-
Ehnert, I. (2009).
Manajemen Sumber Daya Manusia Berkelanjutan: Analisis Konseptual dan Eksploratif
. Springer. -
Gubler, T., dkk. (2018).
Praktik SDM yang Berkelanjutan dan Hasil bagi Karyawan
. Jurnal Etika Bisnis. -
Kramar, R. (2014).
Di Luar Strategic HRM: Apakah Sustainable HRM Pendekatan Selanjutnya?
Jurnal Internasional Manajemen Sumber Daya Manusia. -
Renwick, D., dkk. (2013).
Green HRM: Tinjauan dan Agenda Penelitian
. International Journal of Management Reviews. -
Forum Ekonomi Dunia. (2023).
Laporan Masa Depan Pekerjaan
.
Disediakan oleh SyndiGate Media Inc. (
Syndigate.info
).